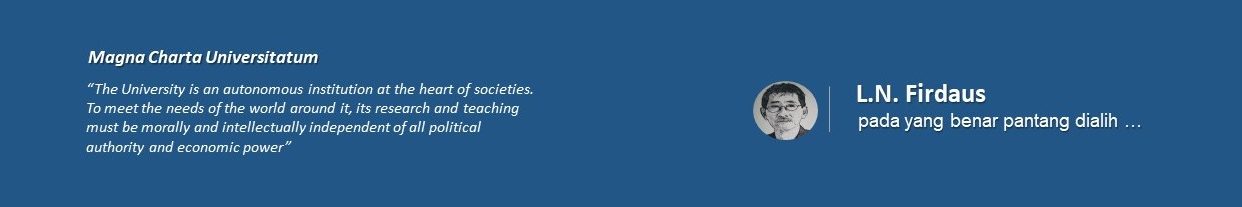Oleh L.N. Firdaus
Alumni Lemhannas RI 2009
Demokrasi, sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, telah dianggap sebagai sistem yang paling inklusif dan adil. Namun, seperti halnya sistem pemerintahan lainnya, demokrasi bukanlah suatu kekebalan dari ancaman dan tantangan. Salah satu fenomena yang semakin mendapat perhatian adalah pembusukan demokrasi (Democracy Decay) menjadi perhatian serius di berbagai belahan dunia.
Pembusukan Demokrasi mengacu pada suatu proses perlahan yang mengikis nilai-nilai demokrasi secara sistematis. Ini bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari penurunan partisipasi politik hingga peningkatan otoriterisme.
Sejumlah definisi dan pemahaman terkait Pembusukan Demokrasi akan membantu kita untuk memahami kerumitan fenomena ini secara lebih mendalam. Levitsky dan Ziblatt (2018), mendefiniskan pembusukan demokrasi sebagai proses perlahan, bertahap, dan seringkali tidak terlihat yang mengarah pada penurunan kualitas demokrasi. Serangan terhadap lembaga-lembaga demokratis, norma-norma politik, dan hak-hak dasar dapat merusak fondasi demokrasi.
Lingkup dari pembusukan demokrasi mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Pertama, adanya ancaman terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Kedua, terjadinya penurunan partisipasi politik, baik dalam bentuk pemilihan umum maupun keterlibatan aktif dalam proses politik sehari-hari. Ketiga, peningkatan korupsi di dalam institusi-institusi pemerintahan, yang dapat merongrong integritas dan kepercayaan publik.
Sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, Demokrasi oleh banyak orang dianggap sebagai sistem paling adil dan inklusif. Namun, pada saat yang sama demokrasi pun rentan terhadap pembusukan sehingga fondasi demokrasi mengalami kerapuhan.
Pembusukan demokrasi merujuk pada proses yang perlahan tapi pasti, di mana nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan keadilan tergerus secara sistematis. Ini bisa terjadi melalui berbagai macam, cara, termasuk penurunan partisipasi politik, pembatasan kebebasan pers, keterlibatan korupsi dalam sistem politik, dan peningkatan otoriterisme.
Pembusukan demokrasi menjadi ancaman serius terhadap kekuatan fondasi demokrasi yang sehat. Korupsi politik menjadi salah satu pemicu utama pembusukan demokrasi. Menurut Huntington (1968), korupsi dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis dan menghasilkan ketidakstabilan politik. Ketika pemimpin politik terlibat dalam praktek-praktek korup, perasaan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat dapat memicu ketidakstabilan politik.
Saat elit politik terlibat dalam praktik-praktik korup, kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis dapat runtuh. Korupsi bukan hanya mengancam integritas demokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan.
Polaritas yang meningkat di dalam masyarakat dan di antara partai politik juga dapat menyebabkan pembusukan demokrasi. Ketika pemimpin politik lebih fokus pada perpecahan daripada persatuan, proses pengambilan keputusan menjadi sulit, dan kompromi sulit dicapai. Polarisasi politik yang tinggi dapat melemahkan kapasitas demokrasi untuk mencapai kesepakatan yang melayani kepentingan bersama.
Polarisasi politik yang tinggi dapat merusak proses demokratis dengan memperumit pembuatan keputusan dan menghambat kemampuan untuk mencapai konsensus. Levitsky dan Ziblatt (2018) menyatakan bahwa polarisasi yang ekstrem dapat memicu konflik politik yang berdampak buruk pada stabilitas demokrasi.
Penyebaran berita palsu dan manipulasi media dapat merusak integritas pemilihan dan mempengaruhi opini publik. Manipulasi media dan penyebaran berita palsu dapat meracuni proses demokratis. Sunstein (2017) menyoroti pentingnya kebebasan informasi yang akurat dalam menjaga kesehatan demokrasi. Manipulasi informasi dapat merusak pondasi demokrasi dengan mendistorsi pemahaman masyarakat tentang realitas politik.
Pembusukan demokrasi secara langsung berkontribusi pada penurunan partisipasi politik. Dengan merosotnya kepercayaan masyarakat pada sistem, banyak yang menjadi apatis dan menarik diri dari proses politik (Norris, 2011). Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada proses politik, partisipasi pemilih niscaya akan menurun.
Pemerintah yang terlibat dalam pembusukan demokrasi cenderung membatasi kebebasan sipil, termasuk hak berkumpul, kebebasan pers, dan hak berbicara. Peningkatan otoriterisme yang terkait dengan pembusukan demokrasi seringkali diiringi dengan pembatasan terhadap kebebasan sipil. Freedom House (2020) mencatat penurunan kebebasan sipil di beberapa negara sebagai hasil dari pembusukan demokrasi.
Pembusukan demokrasi juga dapat memperkuat ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Pemimpin yang korup dan terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat (Piketty, 2014).
Menguatkan institusi-institusi demokratis adalah langkah krusial dalam melawan pembusukan demokrasi. Keberadaan sistem peradilan yang independen, badan pengawas pemilihan yang kuat, dan lembaga-lembaga demokratis lainnya dapat menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman (Diamond & Morlino, 2005). Institusi yang kuat adalah kunci untuk melindungi demokrasi dari ancaman internal dan eksternal.
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip demokrasi dan pentingnya partisipasi politik juga dapat membantu melawan manipulasi informasi. UNESCO (2019) menekankan pentingnya pendidikan politik yang mendalam untuk membangun masyarakat yang kritis dan berpartisipasi.
Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses politik dapat memainkan peran penting dalam mencegah pembusukan demokrasi. Inisiatif warga dan kelompok advokasi dapat menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan politik yang korup. Keterlibatan masyarakat adalah benteng pertahanan terkuat terhadap pembusukan demokrasi.
Walhasil, pembusukan demokrasi adalah ancaman serius yang memerlukan perhatian global. Dengan memahami faktor-faktor yang memicu dan dampak dari pembusukan demokrasi, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk melawannya. Melalui penguatan institusi demokratis, pendidikan politik yang kuat, dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat memastikan bahwa demokrasi tetap menjadi sistem pemerintahan yang melayani kepentingan semua warganya. ***